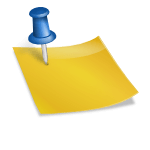Makasar memang panas. Apalagi di pertengahan tahun seperti ini. Luar biasa. Tak mengherankan. Kota yang bernama lain Ujung Pandang ini adalah kota pantai, yang terletak di ujung pulau Sulawesi. Namun, ada yang berbeda kali ini. Saat pesawat yang membawaku terbang ke kota itu mendarat, hujan menyambut kedatanganku, dan membuat udara di bandara Hasanudin terasa sedikit basah.
Kunjunganku ke Sulawesi Selatan kali ini untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi siswa dan mahasiswa tunanetra. Sebuah ihtiar untuk mengakselerasi proses kaderisasi dan pemerataan upaya peningkatan kualitas hidup tunanetra di negeri ini.
Setelah lelah bekerja selama lebih dari empat hari di Pucak, sebuah desa yang berada di Kabupaten Maros, kurang lebih satu jam dari Makasar, aku menghabiskan setengah hari terakhirku untuk jalan-jalan, menikmati pantai di Makasar.
Tujuanku kali ini adalah Pulau Khayangan. Seperti kegiatan jalan-jalanku di Makasar sebelumnya, kali ini aku juga ditemani teman-teman tunanetra dan para volunteer yang menjadi sighted guide kami. Di samping teman-teman lokal, aku juga pergi bersama redaktur diffa yang lain, Irwan Dwi Kustanto, yang biasa mengasuh rubrik sastra. Sejak tahun ini, Irwan yang kini juga menjadi motivator untuk sesama tunanetra selalu kulibatkan dalam pelatihan kepemimpinan yang kuselenggarakan di daerah. Kehadiran Irwan di acara jalan-jalan kami tidak hanya membuat jumlah rombongan jadi lebih banyak “ tujuh orang, tapi, sosoknya sebagai penyair juga memberi rasa tersendiri dalam perjalanan kami. Berikut ini kisahnya.
Pelabuhan Kargo Yang Sibuk.
Setelah mengisi perut kenyang-kenyang di Warng Padaidi yang artinya Warung Kita-Kita, kami segera meluncur ke pelabuhan. Kami tiba di sana sekitar pukul 3.30 sore. Pelabuhan yang persis berhadapan dengan Pulau Khayangan itu adalah pelabuhan kargo. Kapal-kapal besar penuh bermuatan barang memadati tempat itu. Ini mencerminkan kesibukan dunia perdagangan di selatan pulau Selebes ini.
Sepanjang pelabuhan, berjajar kantor-kantor perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL). Untuk memfasilitasi para pengguna pelabuhan, sederetan rumah makan dan tempat hiburan ada di sana. Dari yang sederhana hingga yang mewah.
Setiba di pelabuhan, kami langsung menuju loket pembelian karcis. Untuk menyeberang ke Pulau Khayangan, pengunjung harus menaiki perahu motor sederhana, yang dapat memuat kurang lebih 40 orang penumpang, dengan posisi duduk saling berhadapan. Harga tiket perahu itu 30,000 rupiah. Tiap satu jam sekali perahu menyeberang dari pelabuhan ke Pulau Khayangan dan sebaliknya.
Saat kami tiba dan membeli tiket, petugas loket mengatakan bahwa perahu terakhir baru saja berangkat. Jadi, kami harus menunggu. Tak apa, karena waktu pun masih terlalu sore untuk menyeberang. Tujuan kami ingin menikmati matahari terbenam di Pulau Khayangan. Itu momentum faforitku.
Benteng Roterdam.
Sambil menunggu, kami memanfaatkan waktu mengunjungi Benteng Roterdam yang terletak persis di seberang pintu masuk pelabuhan.
Benteng roterdam dibangun jaman pemerintah penjajahan Belanda. Seperti halnya benteng-benteng yang dibangun Pemerintah kolonial lainnya, Benteng Roterdam juga terletak persis berhadapan dengan laut. Dengan posisi seperti ini, tentara kolonial akan dengan mudah melihat siapa yang datang, kawan, atau lawan. Jika lawan atau musuh, tentu saja langsung ditembak. Itu sebabnya, di bagian depan Benteng Roterdam pun ada meriam, yang moncongnya mengarah ke laut Makasar.
Seperti bangunan buatan Belanda pada umumnya, bangunan Benteng ini juga sangat kokoh.
Benteng Roterdam juga dilengkapi dengan ruang-ruang penjara. Saat aku berdiri mengintip di salah satu pintu kokoh berjeruji besi, aku membaui adanya lorong-lorong sempit dan gelap di dalam sana. Terbayang olehku, seperti yang ada di film-film bertemakan perjuangan, para tawanan perang dikurung di dalamnya, dengan luka-luka yang dibiarkan membusuk tak diobati, tak diberi makan, dan untuk mempertahankan hidup mereka harus berebut tikus untuk dimakan.
Salah satu pahlawan yang pernah dipenjarakan di sini adalah Pangeran Diponegoro. Setelah berhasil mengecoh pangeran asal jawa yang gagah berani itu hingga Beliau bersedia berunding, Jenderal De Kock, Gubernur Jenderal pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu membuang Sang Pangeran ke Makasar hingga Beliau wafat di kota Angin Mamiri ini.
Ada yang unik dari Benteng Roterdam. Di antara ruang-ruang yang ada di benteng tersebut, ada jalan menuju ke luar benteng menembus pagar beton yang kokoh. Jalan itu mendaki, tak terlalu curam, berbentuk seperti ram untuk para pengguna kursi roda.Wah, jalan ke luar di sini aksessibel, kata Hamzah, tunanetra salah seorang anggota rombongan kami. Saat jalan ke luar itu menembus benteng, dinding dan atap berbentuk melengkung seperti sebuah pintu gerbang. Kuat dan indah.
Di bagian tengah dari gedung-gedung benteng yang berbentuk menyerupai huruf U itu terdapat taman yang asri. Dari bentuk dan penataannya, Tentu saja dapat kita tebak bahwa taman ini bukan peninggalan Pemerintah kolonial. Pengunjung memanfaatkan taman itu untuk berfoto-foto, termasuk kami juga. Di beberapa tembok pembatas rendah di sela-sela tanaman perdu di taman itu, pengunjung memanfaatkannya untuk duduk-duduk melepas lelah. Di sana, kudengar suara-suara yang sedang menjelaskan apa dan bagaimana sejarah Benteng Roterdam.
Pulau Khayangan.
Setelah puas melihat-lihat Benteng Roterdam selama kurang lebih satu jam, kami segera menuju dermaga. Di ujung dermaga kayu itu, perahu telah menunggu kami. Tak ada anak-anak tangga yang bisa kami turuni saat masuk ke dalam perahu. Hanya ada satu jalan turun, agak dalam. Untuk mempermudah memperkirakan kedalaman posisi perahu, Sang kapten “ pengemudi perahu menyarankan kami para tunanetra untuk duduk terlebih dahulu, baru kemudian menurunkan kaki memasuki perahu.
Tak perlu menunggu hingga perahu penuh penumpang. Begitu seluruh rombongan kami berada di dalam, perahu itu pun langsung bergerak menuju Pulau Khayangan.
Ambe Mange ri Pulau Khayangan! “ Ayo Pergi ke Pulau Khayangan!
Perahu motor itu berjalan tak terlalu cepat, sehingga kami dapat menikmati perjalanan laut ini. Dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk menuju Pulau Khayangan.
Pulau khayangan adalah satu dari gugusan pulau-pulau kecil di sebelah barat kota pelabuhan Makasar. Berukuran kurang lebih satu hektar, dan berpasir putih. Pulau kecil ini masih dikelola dengan cara sangat sederhana. Ada penginapan dan rumah makan, yang sekaligus berfungsi sebagai tempat duduk-duduk menikmati laut. Saat kami datang, hanya sedikit pengunjung di sana. Ini tentu menguntungkan bagi kami. Suasana tenang, dan kami dapat menikmati pantai Pulau Khayangan sepenuhnya.
Saat menginjakkan kaki di Pulau Khayangan, kerangka buaya yang ditempatkan di dalam akuarium kaca menyambut kedatangan kami. Penduduk asli meyakini buaya itu dahulu tersesat di muara sungai hingga masuk ke laut, dan akhirnya mati. Untuk mengabadikannya, kerangka tubuh yang masih utuh binatang reptil itu diawetkan di dalam kotak kaca untuk dijadikan tontonan pengunjung pulau.
Sebelum menyeberang, kami telah menyiapkan bekal, sekantong plastik kue Barancong; kue tradisional terbuat dari campuran kelapa dan tepung trigu, rasanya gurih. Di Jawa, kita menyebutnya Kue Pancong. Sambil menunggu senja turun, sebagian rombongan duduk-duduk di tempat yang disediakan untuk pengunjung beristirahat. Aku dan Arifin, tunanetra low vision yang baru saja menyelesaikan pendidikan tingginya — ia seorang sarjana sastra Inggris — berdiri di pagar tembok menikmati laut.
Baru Beberapa saat kami di sana, memandangi cakrawala, aku mendapati sang surya mulai beranjak menuju peraduannya. Aku tak mau melewatkan momentum ini, Segera saja kuajak Fitra “ salah seorang volunteer pendamping kami “ dan Irwan menuju tempat yang lebih terbuka. Dengan kamera poket yang kami bawa, kami abadikan momentum indah lukisan Ilahi ini.
Dengan sabar, kami menyaksikan, perlahan tapi pasti, bumi bergerak dan menenggelamkan matahari. Cahaya terangnya perlahan menguning, memerah, lalu, langit mulai berwarna abu-abu. Kurasakan pula, udara menjadi lebih sejuk, udara senja. Bagiku, ini prosesi alam yang sangat menyentuh. Ada keharuan saat menyaksikan matahari meredup dan akhirnya menghilang. Ada kerendahan hati, merasakan Kebesaran Tangan yang menggerakkannya.
Setelah puas menemani sang menari menuju tempat peraduannya, kami segera turun ke laut untuk menyambut datangnya malam. Pantai di seputar laut Makasar tak seperti pantai di pulau jawa. Di pantai selatan jawa, misalnya Anyer, atau pangandaran, suara ombak berdebur-debur, menghempas, sangat menggairahkan. Di Pulau Khayangan ini, ombak hanya beriak-riak lembut menyentuh kaki-kaki kami.
Begitu kakiku menyentuh sejuknya air laut yang masih sangat jernih, dan rambutku bergerak-gerak lembut oleh hembusan angin laut, segera kusapa dia, dengan teriakan lantang. Hai lauuuuuuuuut¦¦ Aku datang padamuuuuuuuu¦¦ Sambutlah akuuuuuuu¦¦ Sambil menyapa, perlahan aku bergerak ke air yang lebih dalam. Dan air asin itu mulai membasahi celana jins yang telah kugulung hingga hampir mencapai lutut. Saat berjalan di air, kurasakan sesuatu yang lembut menyentuh kaki-kakiku. Setelah kuraba, karena ingin tahu apa itu, ternyata tanaman laut berdaun merah yang tumbuh di atas batu-batuan, cantik sekali. Di saat yang sama, kudengar teriakan-teriakan dari anggota rombongan lain. Arifin meneriakkan impiannya, ingin jadi apa ia sepuluh tahun nanti. Sedangkan Hamzah, melantunkan lagu-lagu khas Makasar, yang diiringi dengan musik akapela oleh anggota rombongan yang lain. Semuanya gembira, melepas lelah setelah bekerja keras selama beberapa hari terakhir.
Tapi, di antara rombongan yang mengekspresikan kegembiraan dengan teriakan-teriakan, ada yang tak banyak bersuara. Mau tahu, siapa dia? Sang Penyair, Irwan. Dalam diamnya menikmati datangnya malam di Pulau Khayangan, sebait puisi dilahirkannya. Dan ia memilih Mutmainnah, yang biasa disapa Innah, salah seorang volunteer bersuara lembut, membacakan puisi itu untuk kami semua.
Matahari yang kau lihat tadi, Adalah matahari yang kutitipkan padamu. Debur ombak yang menaiki kaki-kakimu, Adalah ombak yang kuselipkan pada rambutmu. Sekali-kali jangan kau tinggalkan senja dengan matahari dan ombak khayanganmu, Karena aku tak punya apa-apa lagi untuk menatapmu dan , Menyelipkan kata-kata cinta di hatimu.
Puisi romantis Irwan yang dibacakan dengan lembut oleh Innah mengakhiri kunjungan kami di Pulau Khayangan. Rombongan segera menuju perahu yang membawa kami kembali ke pelabuhan Makasar. Lampu-lampu menghiasi pantai Makasar di malam hari. Suara musik berdentum-dentum pun mulai terdengar. Selamat tinggal Pulau Khayangan. *Aria Indrawati