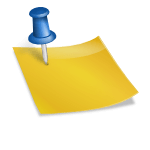Menjadi disabilitas Sensorik netra tidak semenyedihkan apa yang dipikirkan orang-orang awam di luar sana, tidak semengerikan apa yang saya kira juga. Menjadi disabilitas sensorik netra hanya berarti harus melihat dengan tangan, melihat dengan telinga, melihat dengan semua organ yang masih berfungsi baik.
Saya berusia delapan belas tahun sekarang. Empat tahun lalu kira-kira, tepatnya di awal tahun 2017 penglihatan saya mulai kabur. Ini bukan hal yang mendadak, tapi cukup buruk untuk membuat orang tua dan keluarga saya panik. Dua tahun sebelumnya, di 2015 dokter sudah mendiaknosa ssaya terjangkit virus tourch plasma, dan memberi tahu kami bahwa penglihatan saya akan menghilang perlahan demi perlahan. Virus yang saya dapat dari intensitas bermain saya yang over bersama kelinci itu menyebabkan uveitis katarak komplikata pada mata saya, sebuah kondisi di mana lapisan mata menempel hingga membuat keruh kornea. Kemungkinan dioperasi dan sembuh seperti sediakala tidak ada. Karena kata dokter, mata saya seperti buku yang basah. Jika dipaksakan untuk dibedah, berarti dokter harus membuka lapisan-lapisan yang sudah lengket. Kemungkinan besar, seperti kertas basah, mata saya akan robek fatal karena tindakan tersebut.
Orang tua saya sempat ngotot ingin menjalani pengobatan. Dua tahun bolak-balik rumah sakit, tiga kali operasi, belasan kali mendapat gelengan dokter … akhirnya fix mata saya buta total. Ini tidak begitu buruk untuk saya, mungkin karena saya masih terlalu muda saat itu, empat belas tahun dan belum mengetahui banyak hal tentang kesulitan-kesulitan disabilitas. Anak umur empat belas tahun … yang terbiasa ditimang-timang, terbiasa bersembunyi di bawah kehangatan orang tua. Anak tunggal yang tidak pernah merasakan penolakan sama sekali … mana tahu soal stigma? Mana tahu bahwa menjadi buta, berarti harus menghadapi stigma segudang dari masyarakat. Mana tahu tentang menjadi buta, berarti harus menanggung penolakan dan pengucilan dari masyarakat. Saya tidak tahu itu semua, tapi orang tua saya tahu. Itu mungkin yang kemudian menggerakan orang tua saya untuk mengupayakan segala hal terbaik untuk saya, dalam masa transisi ke kondisi disabilitas sensorik netra.
Tahun 2017, saat penglihatan saya mulai kabur, orang tua sigap mencarikan yayasan atau Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bisa menerima anak buta untuk bersekolah. Mama mendapatkan SLB yang menerima murid disabilitas sensorik netra beberapa bulan kemudian, meminta persetujuan bapak untuk memidahkan saya dari sekolah yang lama ke SLB, lalu menemani saya untuk menengok suasana SLB. Saya akhirnya pindah sekolah. Bapak membelikan laptop untuk saya, karena kata mama disabilitas sensorik netra belajar harus dengan laptop. Dan jadilah waktu itu saya resmi pindah SMP ke SLB A/YAPTI Makassar.
Sebelum menjadi disabilitas sensorik netra, saya suka melukis. Kakek buyut saya seorang pelukis profesional, bakatnya itu kemudian dia wariskan kepada mama saya. Dari sanalah mungkin bibit awal kepandaian saya melukis tercipta. Saya mencintai kanfas dan kuas seperti saya mencintai semua dongeng-dongeng kehidupan. Dengan melukis, seolah-olah saya bisa bercerita ke orang-orang yang melihat lukisan itu tentang banyak hal. Tentang kebahagiaan saya dilahirkan ke muka bumi ini, tentang perceraian orang tua saya yang tidak pernah saya permasalahkan, tentang betapa saya sebenarnya menyayangi bapak dan mama. Saya bukan anak yang pandai berkata-kata, dari lukisan-lukisan kemudian rasa sayang saya kepada mama dan bapak saya sampaikan.
Satu-satunya hal yang membuat saya sedih ketika menjadi disabilitas sensorik netra adalah karena saya tidak bisa melukis lagi. Saya dimasukkan ke asrama khusus disabilitas sensorik netra, saya sekolah di sana, dan saya tidak membawa kanfas dan kuas-kuas saya. Bukan karena dilarang pihak asrama, tapi karena saat itu penglihatan saya sudah sangat kabur sekali, sampai-sampai saya tidak bisa lagi melukis dengan baik. Warna-warna yang saya lukis di atas kanfas akan saling tumpang tindih, tidak enak dilihat. Maka saya memutuskan untuk berhenti melukis. Itu berat sekali … apalagi karena saya tidak memiliki keahlian lain kecuali melukis. Suara saya jelek, kemampuan bermain alat musik saya rendah, dan saya bukan tipe anak yang mudah meluapkan apa-apa dengan kata-kata.
Masuk di SLB, saya bertemu banyak teman baru dan banyak orang tua baru. Di YAPTI (Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia), kemudian saya belajar membaca huruf braille. Tidak begitu sulit menulis huruf braille, tapi sulit sekali membacanya. Jari-jari saya kaku, dan kalau saya memaksakan membaca hingga larut malam, besoknya saya akan terbangun dengan tangan yang pegal-pegal. Padahal saya baru menjadi disabilitas sensorik netra, saya suka menyimak cerita, dan satu-satunya cerita yang akses untuk disabilitasnetra saat itu yang saya ketahui hanya cerpen-cerpen di majalah GEMA BRAILLE.
Suatu pagi, kira-kira dua minggu setelah tinggal di asrama, saya terbangun karena suara seseorang yang berbicara dengan nada yang hangat. Saya meraih handphone, melihat jam, masih terlalu pagi. Saat itu saya sudah menggunakan handphone, tapi hanya untuk menelepon, mengirim pesan ke keluarga dan teman-teman, atau untuk memposting sesuatu di media sosial. Saya belum memanfaatkan handphone dengan maksimal.
Saya duduk dan mendengarkan suara yang berasal dari laptop teman kamarku di asrama itu. Agak lama mendengarkan, saya baru mengerti kalau suara yang menyenangkan dan lues itu sedang bercerita. Kedengarannya seperti membaca novel. Tidak beberapa lama, teman yang dari laptopnya mengalun suara seseorang yang membacakan novel itu terbangun. Rupanya tadi dia menyalakan laptop dan tertidur karena bacaan novel. Dia mematikan laptopnya, la bersiap untuk mandi dan ke sekolah. Saya masih baru di asrama itu, masih malu untuk bertanya, tapi saya berniat untuk menyiapkan diri untuk mempertanyakan suara orang membacakan novel tadi kepada teman baru saya.
Beberapa hari kemudian, saat berada di sekolah dan ingin kembali ke asrama, saya mendapati teman saya lagi-lagi mendengarkan suara orang yang membacakan novel untuknya. Saya berhenti di depan lab komputer, di dalam sana ia asyik mendengarkan suara-suara yang keluar dari laptopnya. Saya bertanya-tanya sendiri apa sebenarnya yang dia dengarkan. Apakah itu adalah saudaranya yang menyisihkan waktu membacakan buku untuk adiknya yang buta? Ataukah itu adalah mitra yang memang khusus diminta untuk membacakan novel? Saya salut sekali kalau memang ada orang yang berbaik hati membacakan buku untuk adik atau temannya yang tidak bisa membaca novel dengan nyaman.
Masuk ke lab komputer, duduk di samping teman itu, saya memandangi layar laptopnya yang terbuka. Saya masih bisa melihat meski sudah kabur. Saya bertanya ke teman saya, apa itu? Dia kemudian menjelaskan tentang audio book, tentang DTB, tentang Mitra Netra. Selama dia menjelaskan, mulut saya membulat dan mengagumi betapa teknologi memudahkan orang untuk berbuat baik ke orang-orang lainnya. Membacakan buku dan direkam … kemudian rekamannya bisa didengarkan banyak disabilitas sensorik netra. Ide yang sangat bagus ….
Sejak hari itu, masa-masa awal saya menjadi disabilitas sensorik netra diisi oleh audio-audio book dari Mitra Netra. Kesukaan saya adalah buku ‘Daun Yang Jatuh Tidak Membenci Angin’, dan buku-buku karya Rama Aditia Adikara. Satu lagi … saya juga suka dengan buku ‘negeri lima Menara’. Soal suara, saya suka semua suara orang yang menjadi pembaca novel di Mitra Netra. Bagi saya mereka semua sama saja. Sama-sama orang baik yang mungkin sengaja diturunkan Tuhan untuk membuat saya bisa menikmati cerita lagi, meski bukan melalui lukisan.
Sekarang, saya sudah tidak menggunakan laptop dan otomatis dengan begitu tidak bisa lagi mendengarkan koleksi audio book di laptop saya dulu. Tapi saya bersyukur pernah tidak sengaja mendengar audio book teman saya, lalu kemudian jatuh cinta dengan metode membaca Mitra Netra. Lebih seringnya sekarang saya membaca buku digital di handphone, dengan suara voice over yang kecepatannya saya atur ke tingkat 100%. Sensasinya tidak semembahagiakan sewaktu mendengar audio book dari Mitra Netra, memang.
Sekarang, saya sudah tidak melukis lagi dan saya tetap seperti dulu, sulit untuk berbicara. Saya selalu canggung, selalu gugup juga saat ingin mengungkapkan perasaan melalui lisan. Dan syukurnya melalui pagi di mana saya mendengar audio book secara tidak sengaja itu, saya menjadi tahu bagaimana bisa bercerita kembali. Bukan dengan lisan, bukan dengan lukisan. Tapi dengan tulisan. Dan beginilah mungkin peran besar Mitra Netra yang bisa saya ceritakan, yang bisa saya ingat sampai jauh-jauh hari nanti.
***
Nabila May Sweetha
Juara Favorit Lomba Menulis Essai dalam Rangka Peringatan HUT Yayasan Mitra Netra ke-30