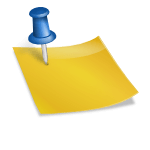Waktu masih menunjukkan pukul 8.30 pagi, tapi udara terasa begitu panas. Tak heran, karena minggu pagi itu aku berada di Makasar. Baru beberapa menit meluncur dari hotel tempatku menginap ke YAPTI (Yayasan Pengembangan Tunanetra Indonesia) sebuah lembaga tempat di mana para tunanetra di Makasar membekali diri dengan ilmu dan ketrampilan,kerongkonganku mulai terasa kering. Kuteguk air mineral beberapa kali untuk membasahinya, dan, sisa-sisa jus markisa yang sebelumnya masih terasa di lidahku segera lenyap, tersapu air penawar dahagaku.
Kepergianku ke Makasar bukan untuk liburan. Pagi itu aku akan bertemu mahasiswa tunanetra, generasi muda yang banyak orang menyebutnya sebagai “calon penerima tongkat estafet kepemimpinan kelak”. Untuk mereka kubawakan sembilan buah komputer mini berlayar delapan inci; sudah tentu dilengkapi dengan software pembaca layar.
Apa yang kulakukan ini merupakan bagian dari gerakan kampanye global bertajuk “Higher Education For Blind Students” yang dimotori oleh ICEVI (International Council of Education for People With Visual Impairment); sebuah jaringan kerja sama berskala global yang berupaya meningkatkan partisipasi dan kualitas tunanetra di bidang pendidikan. Melalui kampanye global ini, ICEVI berupaya mendorong lebih banyak tunanetra di negara-negara sedang berkembang dapat menempuh pendidikan tinggi dengan menyediakan fasilitas alat Bantu teknologi yang mereka butuhkan, agar tunanetra dapat belajar lebih mandiri, berprestasi lebih baik dan menyelesaikan studi tepat waktu.
Gerakan kampanye yang dimulai pertengahan tahun 2006 ini dilakukan, karena keprihatinan ICEVI pada lambatnya proses peningkatan kualitas hidup tunanetra di negara-negara sedang berkembang. Dari hasil studi yang mereka lakukan, diketahui penyebabnya adalah karena sebagian besar tunanetra hanya dapat menikmati pendidikan dasar, sebagian lainnya pendidikan menengah, dan sangat sedikit yang mampu menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi.
Di wilayah Asia Tenggara, kampanye ini diujicobakan di tiga negara; Indonesia, Filipina dan Vietnam. Di Indonesia, ICEVI berpartner dengan organisasi local yaitu Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), dan sebagai tunanetra yang telah mengenyam pendidikan tinggi dan merasakan besarnya manfaat pendidikan dalam kehidupanku, aku sangat bangga mendapatkan kepercayaan mengkoordinir kegiatan ini. Yang lebih membuatku bangga, Indonesia adalah negara yang pertama kali dipilih untuk uji coba.
Secara pribadi, Makasar adalah salah satu kota impianku. Aku mengharapkan kota yang terletak di ujung selatan pulau Sulawesi ini tidak lama lagi akan menjadi pusat pemberdayaan tunanetra untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya, aku perlu memberikan perhatian ekstra di sana. Dan, kedatanganku untuk kesekian kalinya di kota angin mamiri minggu pagi itu adalah salah satunya.
Hanya, ada satu hal yang membuatku sangat prihatin. Dari sepuluh orang tunanetra yang menempuh pendidikan tinggi di tahun akademik ini, hanya ada satu perempuan. Kusampaikan keprihatinanku ini saat aku bertemu para aktivis tunanetra yang gigih memperjuangkan perlindungan, penghargaan dan pemenuhan hak-hak para tunanetra di sana. Dan, mereka pun mengakui bahwa partisipasi perempuan tunanetra di bidang pendiddikan di Sulawesi memang masih sangat rendah. Di YAPTI sendiri, dari kurang lebih empatpuluh siswa yang belajar di sana, hanya ada sepuluh siswa yang perempuan.
Ini bukan berarti jumlah perempuan tunanetra hanya sedikit. Apa yang terjadi di Sulawesi itu juga merupakan cerminan kondisi Indonesia secara umum. Hanya Jawa yang sedikit lebih baik, selebihnya, masih sangat memprihatinkan.
Perempuan tunanetra, sebagaimana halnya perempuan penyandang kecacatan lainnya, mengalami diskriminasi ganda. Hal ini makin kita rasakan saat berada di daerah yang jauh dari kemajuan teknologi. Masih ada angapan yang dibentuk oleh budaya masyarakat bahwa, orang yang menyandang kecacatan, termasuk tunanetra, adalah “mahluk yang tidak berdaya”. Dan, apabila si penyandang cacat itu perempuan, maka, “stigma mahluk tak berdaya” itu menjadi berlipat-lipat.
Akibatnya, perempuan tunanetra tidak menjadi “prioritas” untuk mendapatkan pendidikan. Dalam keadaan tidak berpendidikan, mereka semakin tidak berdaya; tidak mandiri secara ekonomi, menjadi beban keluarga, dan, harus menerima saja kondisi itu tanpa perlawanan. Tidakkah ini mirip dengan jaman saat Kartini masih hidup?
Menurutku, ini salah satu bentuk “kekerasan budaya” pada perempuan tunanetra. Selama ini, jika banyak orang bicara soal kekerasan pada perempuan, kita hanya berfokus pada “kekerasan fisik”, dan seringkali mengabaikan “kekerasan budaya”. Padahal, kekerasan yang dilakukan oleh “budaya” berdampak sangat luas; korbannya adalah mereka yang berada di lingkungan penganut budaya tersebut.
Sadar akan kondisi ini dan ingin berperan mengatasinya meski hanya peran kecil, aku tidak menolak saat beberapa teman aktivis di Makasar memintaku memberikan motivasi pada beberapa siswa perempuan tunanetra di YAPTI. Targetku sederhana saja, membuat mereka mau bicara dari hati ke hati denganku, menumbuhkan motivasi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, serta memberi gambaran apa yang kelak bisa mereka lakukan jika mereka berpendidikan dengan baik. Aku juga sangat sadar bahwa sebagian besar dari mereka memiliki masalah keuangan; itu juga yang membuat mereka makin tidak berani bercita-cita. Meski aku tahu itu tidak mudah, aku masih “sedikit” berharap, cerita sukses beberapa perempuan tunanetra tentu saja yang ada di Jawa dapat mendorong mereka “mulai merajut impian”.